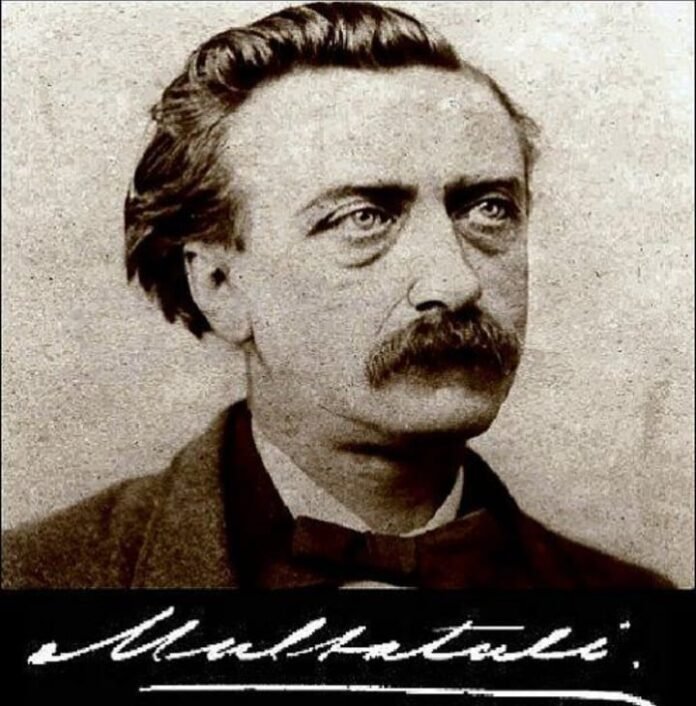Oleh : Ade Irwansyah
LIBUR akhir pekan yang panjang kali ini saya habiskan di rumah sakit. Rencana liburan ke rumah mertua bareng anak-anak yang sudah kami rencanakan batal.
Meski begitu, berkahnya, mungkin saya jadi bisa istirahat. Dan menonton film yang sesuai selera. Bukan menonton film sebagai pekerjaan… Hehehe..
Advertisement