Cerpen : Marlin Dinamikanto
“Seru,” katanya
“Saru,” tanggapku
“Kok?” protesnya.
“Ya, mboh,” jawabku
Begitulah dialog singkat sebelum dia mangkat. Di sebuah grup percakapan media sosial yang tidak begitu ramai pesertanya. Siapa menyangka, itu percakapan terakhir yang begitu singkat. Membuat aku benar-benar merasa kehilangan. Terlebih di percakapan pribadi yang terakhir dia minta didoakan. Didoakan? Masak sih minta didoakan oleh seorang yang dia tahu di sepanjang hidupnya tidak pernah berdoa?!.
Tapi aku sudah berjanji dalam hati, tidak pernah aku sampaikan secara lisan, bahwa aku akan menyimpan segala polemik dan percakapan yang pernah ada. Bukan karena nilai kenangan romantis yang tersaji beserta foto dan ribuan kumbang yang berdengung di ruang komentar.
Bukan itu tujuannya. Melainkan untuk membuktikan, siapa tahu dia benar dan aku salah. Bukan narasi atau argumentasi yang dapat membuktikan benar atau salah. Melainkan waktu yang dapat melindas secanggih apa pun olah kata. Karena waktu disediakan oleh hidup agar kita memilih, dalam hitungan yang terbatas.
Hidup ini memang banyak pilihan. Multiple choice. Namun pada praktiknya hanya ada sedikit pilihan. Kadang kala hanya menyisakan benar dan salah, haram dan halal, hak dan bathil. Mungkin tujuan pragmatisnya untuk lebih memudahkan kerja malaikat Rokib dan Atid dalam menghitung amal dan dosa. Tenane ya embuh.
Bagaimana dengan ghibah? Ibarat burung emprit. Ghibah baginya sudah seperti gabah, butiran buah padi yang belum digiling menjadi beras. Selalu dicari dan dirindukan oleh para penggemar di media sosial. Sehari tidak muncul ghibah hidup laksana daun kering yang berguguran ke tanah.
Berbagi ghibah dalam pandangannya sudah menjadi semacam kewajiban bagi setiap Social Justice Warrior (SJW) – pejuang keadilan sosial dalam praktik sosialisme baru yang mungkin tidak akan pernah dibakukan menjadi sebuah doktrin. Tapi yang nyata dalam pandangan hidupnya, ghibah sudah menjadi kebutuhan pokok. Harus segera dipasok. Tanpa itu hidup terasa landai dan membosankan.
Perut tidak mungkin lapar. Banyak bantuan sosial yang mengalir dari gudang-gudang pemerintah. Tapi percakapan tidak boleh sepi dari ghibah. Sebab ghibah adalah piranti utama untuk membangkitkan pernyataan bahwa manusia itu masih ada. Dalam pertempuran dunia yang tidak nyata. Harus ada alat untuk mengingatkan siapa pun yang berkuasa.
Itu kata dia. Tapi aku selalu menjadi antagonis dari segala ghibah yang dia lontarkan di berbagai platform media sosial. Bagiku manusia akan baik-baik saja tanpa ghibah. Bahkan hidup akan lebih damai, tertib dan tenang seperti suasana perkampungan suku-suku pedalaman.
“Negeri tata titi tentrem loh jinawi kerta raharja” begitu kata Ki Jumali saat mendalang di rumah mas Indro Tjahjono. Tapi Ki Jumali alias Lek Jum dikabarkan sudah wafat beberapa waktu yang lalu.
Mendiang Lek Jum, seperti halnya aku, lebih sering berada di kubu Harmoni. Sedangkan mendiang Si Raja Ghibah berada di kubu yang aku anggap barisan penyebar hoax. Toh demikian hubungan sosial kami, terutama menjelang dia mangkat, baik-baik saja.
Semua bermula saat Petruk yang berpasangan dengan Bilung rebutan jabatan presiden melawan Jenderal Togog yang berpasangan dengan Gareng. Sejak itu terjadi adu ghibah, saling bully dan ejek antara pendukung Petruk dan Togog. Bukan hanya masyarakat Republik Karang Kedempel yang terbelah, melainkan juga antara paman dan ponakan, antara sepupu bahkan ada pasangan suami istri karena berbeda pilihan.
Begitu juga dengan aku dan Si Raja Ghibah. Meskipun sejak kecil bersahabat, sering mandi bareng di Sumber Ponjong, cari belut di sawah dan sesudahnya dimasak dengan bumbu seadanya, dan banyak sekali kenangan berserak lainnya juga tidak luput dari perseteruan.
Kenangan yang berserak itu lenyap tak bersisa sejak aku menjadi Tim Sukses pasangan Petruk – Bilung dan dia menjadi Tim Sukses pasangan Togog – Gareng. Mungkin ada sekitar tiga tahun kami saling tidak bertegur sapa.
Setelah pada akhirnya kami kembali bertegur sapa kondisinya sudah tidak lagi sama. Gelas, kata pelawak Junaidi era 1980-an, yen tugel ora isa dilas. Kalau pecah tidak bisa disambung. Begitu juga dengan perasaan kami setelah tiga tahun tidak bertegur sapa. Canggung. Dingin. Angkuh. Acuh tak acuh.
Di tahun keempat suasana kembali cair. Meskipun masih canggung tapi setidaknya kami bisa tertawa bersama. Mengenang kebodohan masing-masing.
“Kalau dipikir-pikir kita masih sama-sama miskin. Kenapa ya sampai segitunya? Demi membela junjungan di atas sana yang sudah pasti junjunganku tidak mengenalku dan junjungannu tidak mengenalmu,” kataku saat mengajaknya makan di Warung Mbok Warsinem, warung langganan sejak kami usia remaja yang kini dikelola oleh cucunya.
“Hehehehe, kau kan lebih dulu mengenalku daripada Presiden Petruk dan aku lebih dulu mengenalmu daripada Pak Jenderal Togog,” balasnya sambil memainkan bola mata yang mirip penari dari India.
Sejak itu kami sepakat hanya bertarung dalam level gagasan. Aib penguasa, ini kataku, sepanjang bisa dibuktikan secara valid bisa diumbar. Tapi dia menyanggah apa tolok ukurnya? Tidak ada. Karena validitas itu dibatasi oleh sudut pandang.
Dan validitas dari sudut pandang kekuasaan lebih tidak bisa dipertanggung-jawabkan karena di sana ada kepentingan, baik gelap maupun terang. “Dan mereka punya peraturan untuk melindungi apa pun yang sedang mereka lakukan.”
Itulah satu di antara polemik yang dikesankan seperti Tom dan Jerry. Padahal di tengah pertikaian yang runcing di antara penggemar, sudah itu kami cipika cipiki di sebuah warung kopi langganan kami berdua. Atau makan sate Mbok Warsinem yang sudah ada sejak kami belum lahir.
*
Sedih juga. Satu per satu kawan sudah mangkat. Termasuk Si Raja Ghibah yang setelah kaki kirinya diamputasi minta didoakan sembuh. Tidak bisa berjalan tidak apa, katanya. Karena dia hanya membutuhkan panca indera dan otak yang waras untuk membongkar aib penguasa.
Aku pun sebisa mungkin berdoa untuk kesembuhannya. Entah kepada siapa. Dan aku merasa berdosa. Dia meninggal dunia justru setelah aku berhari-hari berdoa untuk kesembuhannya.
Aku larut dalam perkabungan. Keluarga mendiang yang sudah lama aku kenal menyambut hangat kedatanganku. Tapi orang-orang yang merasa sebagai SJW terlihat hambar memandangku. Mereka mungkin mengira aku tersesat. Atau bahkan mungkin mengira aku mencari pengaruh untuk pemilihan kepala desa di tahun mendatang.
Mereka tahu, aku yang juga memiliki pengikut besar di antara pertarungan di antara kelompok kecil, menilai perkabunganku hanya pencitraan. Karangan bunga atas namaku yang oleh keluarga mendiang dipajang di teras depan seketika hilang entah dipindah oleh siapa dan ditaruh di mana.
Ribuan orang hadir dalam takziah. Meskipun aku sering terlibat pertengkaran gagasan dengan mendiang namun aku ikut terharu melihat kepergiannya diantar oleh ribuan orang. Di sebuah Kecamatan di Kabupaten Gunungsindur yang berdasarkan statistik 2018 populasi penduduknya tidak sampai 70 ribu jiwa.
Saat aku hendak ikut menggotong keranda yang berisi jasadnya, terjadi insiden, aku dipukul entah oleh siapa. Yang pasti lebih dari satu orang. Saat tiga orang diduga pelaku ditangkap oleh aparat berseragam hansip aku minta dilepaskan.
“Biarlah Pak, tidak apa-apa. Lepaskan saja mereka,” pintaku kepada petugas keamanan bermuka boros karena aku tahu umurnya masih 40-an tapi terlihat seperti 60-an.
“Iya tuh Pak Antok. Mereka tidak tahu kalau Pak Antok dan Almarhum temenan sejak kecil. Mereka tahunya Pak Antok dan Almarhum sering berantem di Medsos,” terang Waluya, guru agama yang juga sudah aku kenal sejak kecil.
Aku pun mengiring jenasah hingga ke pemakaman. Orang-orang yang masih mengingatku sebagai Juara III Deklamasi tingkat kecamatan memintaku baca puisi sebelum jenazah dibaringkan ke liang lahat.
Aku pun dengan persetujuan keluarga maju ke depan.
Sobat
Kenangku tentangmu
Tak kan pernah kering seperti bunga
Begitu lah puisi singkat yang aku bacakan di samping keranda. Istri dan ketiga anaknya langsung menyalamiku. Karena memang hingga sebelum Pemilu Presiden Republik Karang Kedempel tahun 2014 kami bersahabat. Alangkah dahsyatnya Pemilu Presiden 2014 yang bisa memisahkan persahabatan hanya karena perebutan kekuasaan antara Petruk dan Togog.
Tujuh tahun silam anak tertuanya baru lulus SMA, anak nomer dua baru masuk SMP dan anak bungsunya masih taman kanak-kanak. Mereka biasa memanggilku Om Antok. Sekarang anak tertuanya sudah bersuami dan memiliki seorang anak yang lucu.
Tiba-tiba saja. Kenangan di Bulakrantai melintas ingatan. Ketika itu aku dan Agus Hendratmoko, nama asli mendiang yang juga pemilik akun si Raja Ghibah sama-sama ikut Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru atau disingkat Sipenmaru. Sayang, begitu ujian masuk kami ketiduran karena malamnya sama-sama begadang main gitar. Bangun jam 10 siang. Ujian sudah bubar.
“Sudah lah. Kita ini ditakdirkan gemblung sejak belum lahir. Kalau pun ikut ujian pasti tidak diterima. Kita kuliah di swasta saja,” saran dia saat melihatku bingung mau apa.
Kami yang berasal dari keluarga Borjuis Kecil di kampung, kebetulan orang tua kami sama-sama pendatang dari Pasargede yang merajai toko-toko kelontongan di
Kabupaten Gunungsindur, tentu tidak ada persoalan dengan biaya pendidikan. Aku dan Agus pun kuliah di Universitas Islam Karang Kedempel, di Fakultas yang sama tapi beda jurusan.
Tidak menyangka dia mengidap diabetes sejak umur 30-an. Sempat membaik setelah dia bertahun-tahun mengganti nasi dengan kentang. Tinggi dan berat badannya seimbang.
Namun begitu diabetesnya kambuh kondisinya sudah tidak tertolong. Dia meninggal dunia sebelum Pemilu Presiden 2019 yang kembali menampilkan perebutan kekuasaan antara Petruk dan Togog
*
Sang Raja Ghibah sudah mangkat. Tapi muncul raja-raja ghibah yang lain. Tanpa data dan fakta yang akurat, benar salah sebarkan. Sebaliknya di seberang sana tidak kalah sadisnya. Mereka memiliki sarang kumbang yang mendominasi semua lini media sosial.



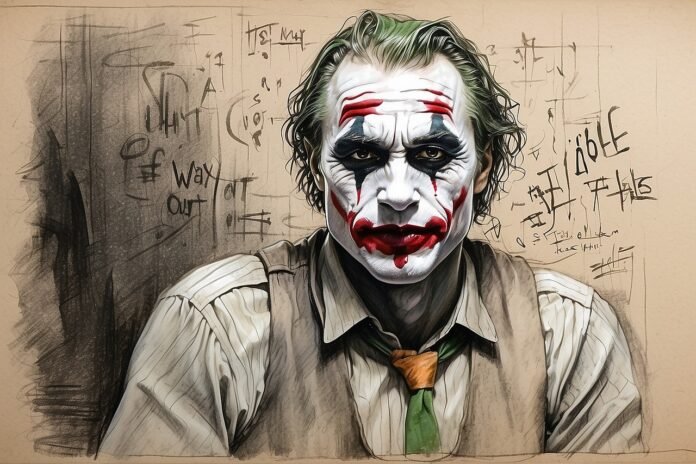










Yang berat itu, endingnya: gua bilang apa? 😁
Betul, hehehee…