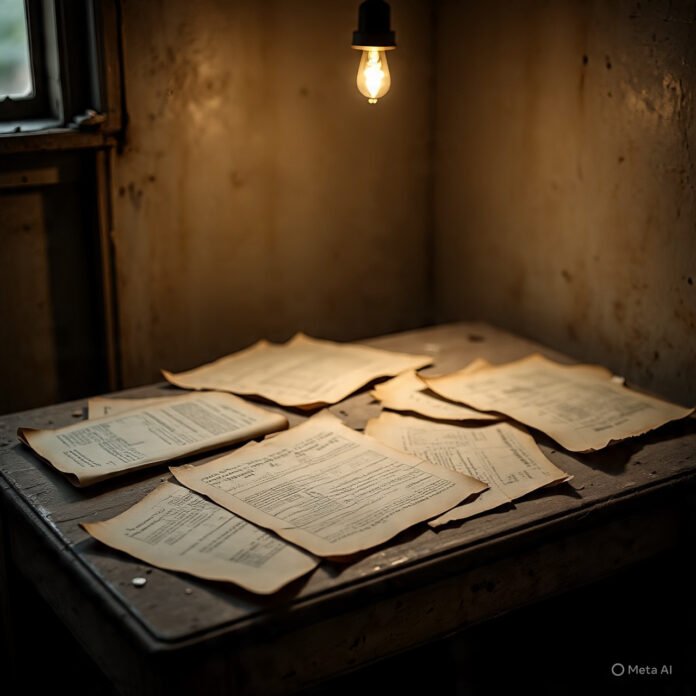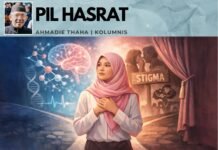Oleh: Radhar Tribaskoro
Dalam perdebatan politik kita sehari-hari—di media sosial, ruang diskusi, hingga meja makan—ada satu frasa yang kini sering muncul: “Mana buktinya?” Bahkan wartawan TV senior seperti Aiman Wicaksono, host acara TV Rakyat Bersuara, tidak lepas dari jebakan frasa itu, repetisinya itu membosankan sekali, “Mana buktinya, mana buktinya.”
Frasa ini memang terdengar wajar. Tapi di balik pertanyaan sederhana itu, ada kebingungan besar. Masyarakat sering menganggap bahwa semua perbedaan pendapat harus bisa dibuktikan dengan cara yang sama seperti di pengadilan. Seolah setiap pendapat politik adalah sebuah tuduhan hukum. Seolah setiap analisis harus menghadirkan bukti fisik yang sah dan tak terbantahkan.
Padahal, dalam kenyataannya, bukti itu punya makna yang berbeda-beda, tergantung pada ranahnya: hukum, politik, atau sains. Dalam dunia sains dan politik, pembuktian tidak selalu berbentuk dokumen resmi, rekaman, atau notulen rapat seperti yang dituntut dalam ruang sidang.
Artikel ini ingin menjelaskan secara sederhana: apa itu “pembuktian”, dan mengapa kita perlu memahami konteksnya sebelum menuntut bukti dari siapa pun.
Pembuktian dalam Hukum
Dalam dunia hukum, pembuktian adalah proses formal yang hanya mengakui jenis bukti tertentu: surat, saksi, keterangan ahli, rekaman, dan barang bukti fisik. Semua itu harus disampaikan dalam prosedur yang sah, di hadapan hakim, dan diuji silang oleh pihak lawan.
Tujuannya jelas: menjaga keadilan bagi semua pihak, dengan menghindari spekulasi atau tuduhan tanpa dasar. Pembuktian hukum bersifat “beyond reasonable doubt” (untuk pidana) atau “preponderance of evidence” (untuk perdata)—dua standar yang tinggi dan sangat spesifik (Siregar, 2015).
Masalahnya, banyak orang awam mengira semua bentuk klaim di masyarakat juga harus tunduk pada standar pembuktian hukum ini. Akibatnya, ketika ada aktivis mengkritik pemerintah, atau analis mengungkap gejala penyalahgunaan kekuasaan, publik buru-buru berkata: “Mana buktinya? Hoaks ya? Jangan fitnah!”
Padahal, seperti dijelaskan oleh ahli hukum Satjipto Rahardjo, “hukum bukan hanya kumpulan peraturan tertulis, tetapi praktik sosial yang terikat konteks” (Rahardjo, 2000). Artinya, tidak semua pernyataan perlu dibuktikan dengan dokumen hukum, terlebih bila konteksnya adalah analisis politik atau kritik sosial.
Pembuktian dalam Politik
Dalam politik, pembuktian bukan soal menang di pengadilan, tetapi soal meyakinkan publik dengan argumen yang rasional dan kontekstual. Politisi, pengamat, atau jurnalis tidak selalu punya dokumen rahasia—tetapi mereka bisa menunjukkan indikasi, pola, dan kontradiksi dari tindakan-tindakan politik yang terbuka di ruang publik.
Contoh:
Jika pemerintah tiba-tiba mengganti pejabat yang sedang menyelidiki korupsi, lalu mengganti UU-nya, lalu melemahkan lembaganya, lalu menyebutnya “reformasi,” maka rangkaian peristiwa itu bisa dibaca sebagai indikasi penguasa bersiap melanggengkan kekuasaannya. Untuk kesimpulan ini, tidak diperlukan bukti materiel seperti akta atau kwitansi.
Ilmuwan politik Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die (2018) menyebutkan bahwa banyak kemunduran demokrasi justru terjadi secara legal dan prosedural, yaitu melalui pembungkaman oposisi, kontrol media, dan manipulasi aturan. Artinya, mekanisme formal bisa disalahgunakan, Dalam hal ini jelas, makna dari suatu rangkaian peristiwa ditemukan dari bagaimana peristiwa-peristiwa itu saling berhubungan, memiliki konteks dan membentuk suatu pola. Jadi, dalam politik makna tidak ditemukan semara dari dokumen legal, tetapi dari penafsiran atas pola-pola yang dibentuk oleh rangkaian peristiwa.
Pembuktian dalam Sains
Sementara itu, dalam sains, pembuktian bersifat terbuka untuk dibantah dan diperbarui. Teori ilmiah tidak pernah final. Ia dianggap sejauh belum ada bukti baru yang meruntuhkannya. Ini disebut prinsip falsifiability oleh Karl Popper (1959), yang menyatakan bahwa klaim ilmiah harus bisa diuji dan dibantah.
Sains tidak menyamakan “tidak punya bukti kuat” dengan “fitnah” atau “hoaks.” Ia justru membuka ruang untuk bertanya, menguji, dan memperbaiki. Seperti ditulis oleh Neil deGrasse Tyson: “The good thing about science is that it’s true whether or not you believe in it.” Namun, kebenaran ilmiah tetap harus tunduk pada proses peer review, pengumpulan data, dan rasionalitas logis.
Kasus Ijazah Palsu
Kesalahpahaman tentang “pembuktian” membuat ruang publik kita kaku dan tidak sehat. Tidak masalah bila hanya orang awam yang keliru, karena itu bisa diluruskan. Celakanya, banyak tokoh dan media berpengaruh ikut terjebak pada pola pikir yang sama: “Mana buktinya?” — seakan-akan setiap perbedaan pendapat adalah tuduhan pidana yang harus diuji di pengadilan.
Persis inilah yang terjadi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tiga tokoh publik—Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa—mengajukan kritik dan keraguan berbasis analisis ilmiah dan temuan empiris, yang seharusnya menjadi bagian wajar dari diskursus politik dan metode sains. Namun, alih-alih dijawab secara transparan, kritik itu diseret masuk ke ranah hukum, dengan tuduhan fitnah dan penyebaran hoaks. Akibatnya, masalah yang semula berada di ranah politik dan sains berubah menjadi perkara hukum, yang justru mematikan dialog dan menghalangi proses klarifikasi publik.
Padahal, secara politik, publik melihat adanya pola kebohongan yang berulang terkait dokumen kesarjanaan Jokowi, yang diperkuat oleh serangkaian tindakan cover-up dari lembaga negara. Mulai dari hilangnya berkas pendaftaran di KPU (Solo, DKI, dan pusat), pernyataan Bareskrim yang merujuk pada bukti koran bermasalah, perampasan arsip media oleh aparat, hingga pembelaan dari UGM yang kehilangan kepekaan ilmiah dan pembiaran Kemendikbudristek atas kemerosotan integritas universitas. Semua ini membentuk rangkaian peristiwa yang saling menguatkan kesan bahwa ada upaya sistematis untuk menutup-nutupi kebenaran.
Dari sudut pandang politik, kasus ini jauh melampaui sekadar keabsahan dokumen. Ia menjadi contoh bagaimana seorang presiden dapat menggunakan kebohongan sebagai metode kekuasaan. Ketika kebohongan diinstitusionalisasi—didukung, atau setidaknya dibiarkan oleh lembaga-lembaga negara—maka demokrasi kehilangan prasyarat dasarnya: kepercayaan publik. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu; ia memerlukan keterbukaan informasi dan kejujuran sebagai fondasi komunikasi politik. Tanpa itu, proses demokratis berubah menjadi formalitas kosong yang dikendalikan oleh narasi palsu.
Seperti diingatkan Hannah Arendt, “Kebohongan yang disengaja, jika dibiarkan, bukan hanya menipu publik, tetapi juga mengubah realitas itu sendiri.” Dalam konteks ini, kebohongan yang dilindungi oleh negara tidak sekadar persoalan etika, melainkan tindakan destruktif terhadap sistem demokrasi. Kasus ijazah palsu Jokowi menunjukkan bahwa ketika kebohongan menjadi instrumen kekuasaan, demokrasi tidak runtuh lewat kudeta atau pembubaran parlemen, melainkan dari erosi kepercayaan dan kebenaran yang berlangsung perlahan namun pasti.===
Cimahi, 10 Ahustus 2025