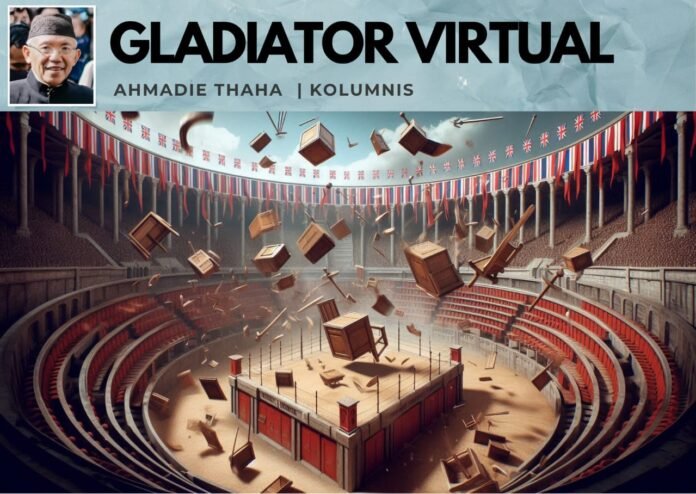Ketika Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, mungkin ia lupa menambahkan catatan kecil: “Yang juga hobi menghujat tetangga hanya karena beda pilihan.” Demokrasi modern, termasuk di Indonesia, telah berevolusi dari debat ilmiah menjadi ajang gladiator virtual. Anda pasti merasakannya —tiap hari, tiap saat.
Contoh terbaru: akhir pekan kemarin, potongan video singkat wacagub Jakarta, Rano Karno, beredar. Ia berkata, “Ini bukan faktor Anies atau Ahok (yang menentukan kemenangan di Jakarta). Ini masyarakat Jakarta. Tiga putaran pun kami pasti menang!” Tak lama kemudian, komentar pedas berhamburan. “Sombong amat!” adalah salah satunya.
Rano dianggap besar kepala, seolah-olah mengecilkan peran Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada Jakarta. Merespons, Geisz Chalifah buru-buru membela. Ia bilang, video itu dipotong di luar konteks, meski komentarnya sendiri agak melantur: “Sama saya saja dia berterima kasih, apalagi dengan Anies.”
Dan begitulah, saling serang di grup WhatsApp pun dimulai. Adu argumen politik kini tak kalah sengit dibanding adu jotos di TPS —tempat kursi melayang atau, dalam kasus ekstrem seperti di Papua, panah-panah melesat. Jika demokrasi disebut sebagai festival gagasan, di sini ia lebih sering menyerupai acara Survivor.
Fenomena kekerasan ini, meski absurd, sudah menjadi “tradisi.” Pilkada Papua diramaikan panah-panah terbang; di Sampang, saksi pilkada dibunuh. Bahkan suasana TPS sering berubah jadi arena seni bela diri. Ironisnya, banyak yang menganggap kekerasan ini sekadar “bumbu” pemilu. Tanpa debat panas di media sosial atau baku hantam di TPS, demokrasi kita terasa hambar.
Di era digital, kekerasan politik menemukan panggung baru: media sosial. Laporan NYU Stern Center, “We Want You To Be A Proud Boy,” menyebut Facebook, Telegram, dan TikTok sebagai medan perang virtual. Algoritma media sosial menyulut konflik lebih cepat dari selebritas menghapus unggahan kontroversial. Dalam lima detik scrolling, kita sudah dihidangi provokasi.
Ketika melihat absurditas ini, solusi sering muncul dengan nada sarkasme. Haruskah TPS dilengkapi ring tinju untuk menyalurkan emosi pendukung? Atau, mungkin kita bisa menciptakan aplikasi “E-Voting Gladiator” —kandidat yang kalah wajib bertarung virtual demi menghibur massa.
Namun, humor gelap ini menyimpan pesan serius, jika kita mau. Laporan NYU Stern merekomendasikan pengawasan konten di media sosial dan pendidikan demokrasi damai. Demokrasi bukanlah UFC. Bukan soal siapa yang paling keras, melainkan siapa yang paling bijak bersikap terhadap perbedaan, terhadap kekalahan dan kemenangan.
Kita dihadapkan pada pilihan: mempertahankan tradisi gladiator politik atau menciptakan festival gagasan yang mencerminkan demokrasi sejati, dilengkapi adu argumen konstruktif tentang Indonesia sebagai negeri maju yang warganya bahagia. Sampai hari itu tiba, mari nikmati drama ini—sambil berdoa agar kursi TPS tidak lagi menjadi peluru yang menyakitkan.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 3/12/2024
Advertisement